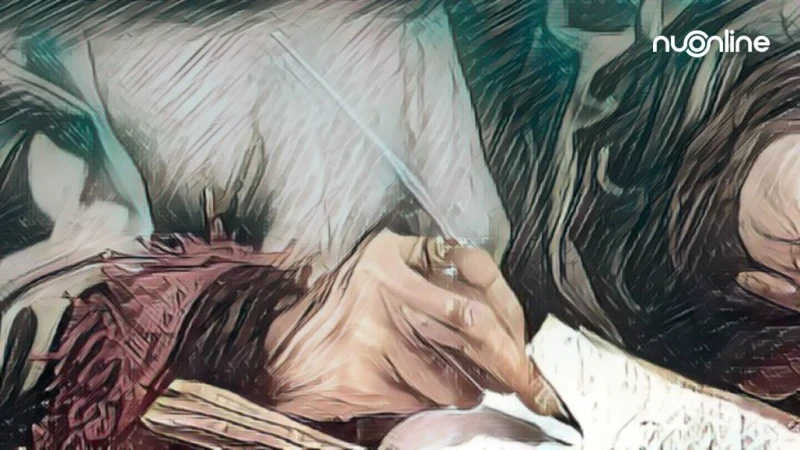Membahas tentang keikhlasan, artinya membahas perihal cara hati dalam menepis dan menolak semua keinginan agar dipuji, dianggap hebat, dan agar mendapatkan posisi khusus dari orang banyak. Dalam ini, hati perlu pembiasaan secara terus-menerus, diuji dengan berbagai rintangan agar tidak menoleh pada manusia. Sebab, tanpa pembiasaan, memiliki hati yang benar-benar ikhlas akan sulit tercapai.
Sebelum manusia menjadikan ikhlas sebagai capaian dalam beramal untuk mendapatkan ridha dari Allah swt, terlebih dahulu ia perlu mengerti perihal pentingnya ikhlas dalam beramal. Dalam Al-Qur’an Allah berfirman,
وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ەۙ حُنَفَاۤءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِۗ
Artinya: “Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar)” (QS Al-Bayyinah [98]: 5).
Pada ayat di atas, Allah memposisikan ikhlas sebagai poin paling penting dalam beribadah, bahkan lebih didahulukan daripada ketaatan. Dengan kata lain, sebelum melakukan ibadah atau amal saleh lainnya, ikhlas seharusnya lebih diperhatikan sebelum melakukan suatu pekerjaan.
Imam Abdul Karim bin Hawazin bin Abdul Malik, atau yang juga dikenal dengan sebutan Imam Qusyairi (wafat 465 H) dalam kitab tafsirnya memposisikan ikhlas di tempat paling atas. Sebab tanpa keikhlasan, semua amal ibadah atau amal saleh tidak bisa diterima oleh Allah, dan hanya menjadi pekerjaan yang tidak memiliki bekas apa pun pada orang yang melakukannya. Lantas, apakah maksud dari ikhlas?
Masih dikutip dari pendapat Imam Qusyairi, ikhlas adalah memposisikan Allah sebagai satu-satunya tujuan tanpa memperhatikan yang lain. Atau, bisa juga diartikan tidak memposisikan selain Allah dalam setiap gerak gerik dan diamnya. Ia murni melakukan suatu amal kebaikan hanya untuk Allah, meski kenyataannya untuk kebaikan bersama, atau bahkan untuk orang lain. Dengannya, semua amal ibadah akan suci dari kekurangan, sehingga dengan gampang diterima oleh-Nya. (Imam Qusyairi, Lathaiful Isyarat ala Tafsiril Qusyairi, [Mesir, Hai’ah al-Mishriah, cetakan ketiga: 1988], juz VIII, h. 95).
Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa semua amal kebaikan tanpa keikhlasan tidak akan sempurna dan tidak memiliki nilai khusus atau bahkan tidak akan memiliki perkembangan. Begitu juga dengan adanya keikhlasan, semua amal kebaikan akan berlangsung terus-menerus dan berkelanjutan.
Untuk mengetahui hal ini, ada banyak tokoh bahkan para ulama yang karyanya hilang ditelan masa bahkan tidak dikaji dan cenderung tidak dihiraukan, meskipun karya-karya tersebut melebih karya yang lain. Namun sebagaimana penjelasan awal, tanpa kehikhlasan semua amal kebaikan tidak memiliki nilai dan tidak akan berkembang.
Kitab Muwattha’ Imam Malik
Kisah ini berawal pada masa Imam Malik bin Anas, tepatnya ketika beliau berupaya untuk mengumpulkan hadits-hadits Rasulullah dalam satu kitab yang kemudian menjadi kitab Muwattha’.
Secara garis besar, upaya pengumpulan hadits bermula sejak masa Rasulullah dan masa sahabat. Hanya saja, pada masa itu belum ditemukan banyak ulama yang berhasil mengumpulkan dalam satu kitab secara khusus. Sebab, mereka lebih fokus pada pengembangan Islam dan upaya untuk mengislamkan kembali orang-orang yang keluar dari Islam (murtad) pasca wafatnya Rasulullah. Oleh karenanya, kitab khusus yang berisi hadits Rasulullah saat itu belum ada, meski ada hanya sebagian yang lebih sedikit saja.
Pada masa tabiin, Imam Malik terinspirasi untuk menuliskan hadits-hadits Rasulullah dalam satu kitab secara khusus, tepatnya ketika Khalifah Abu Ja’far Al-Manshur bertemu dengannya ada musim haji. Ia mengaji perihal hadits Rasulullah kepada Imam Malik setelah melakukan ibadah haji. Melihat penjelasan yang sangat luas dan hafalannya yang sangat kuat, Khalifah Abu Ja’far memohon kepadanya untuk menuliskan kitab khusus yang hanya berisi hadits-hadits Rasulullah.
Kendati permohonan tersebut datang dari seorang khalifah, Imam Malik tidak langsung mengiyakan permintaannya. Sebab menurutnya, setiap orang memiliki metode dan cara tersendiri untuk mengetahui hadits Rasulullah, sehingga tidak layak jika hanya membatasi hadits sebatas yang ada dalam diri Imam Malik. Akan tetapi, pada akhirnya Imam Malik mencoba mengkodifikasi hadits-hadits Rasulullah menjadi satu sembari mencari hadits-hadits lain yang belum beliau ketahui.
Di sela-sela upaya dan perjuangannya untuk mengumpulkan hadits, banyak orang-orang saat itu yang mengomentari dan bahkan hendak menyainginya. Hal itu dengan tujuan agar mendapat pujian dan tepuk tangan dari orang lain. Berbeda dengan Imam Malik, beliau murni ikhlas untuk mengumpulkan hadits dalam satu kitab, tanpa sedikit pun terbesit dalam benaknya untuk mendapatkan pujian dari orang lain.
Kisah ini diabadikan oleh Imam Abdurrahman bin Abu Bakar Jalaluddin as-Suyuthi (wafat 911 H) dalam salah satu kitabnya, bahwa ikhlas memiliki posisi khusus yang tidak akan pernah terkalahkan oleh yang lainnya. Imam Suyuthi mengatakan,
وَقَدْ صَنَّفَ اِبْنُ أَبِي ذَئْبٍ بِالْمَدِيْنَةِ مُوَطَّأً أَكْبَرَ مِنْ مُوَطَّأِ مَالِكٍ حَتَّى قِيْلَ لِمَالِكٍ مَا الْفَائِدَةُ فِي تَصْنِيْفِكَ؟ قَالَ مَا كَانَ لِلهِ بَقِىَ
Artinya, “Sungguh Ibnu Abi Dza’bi di kota Madinah telah menyusun kitab Muwattha’ yang lebih besar dari kitab Muwattha’-nya Imam Malik, hingga ditanyakan kepadanya, ‘Apa faedah dalam karyamu (Muwattha’) ini?’ Imam Malik menjawab, ‘Apa (kitab) yang karena Allah akan abadi’.” (Imam Suyuthi, Tadzribur Rawi fi Syarhi Taqribin Nawawi, [Darut Thayyibah, tahqiq: Syekh Abu Qutaibah], juz I, halaman 89).
Kisah ini mengingatkan kita betapa pentingnya ikhlas dalam beramal, bahkan kitab yang membahas dengan detail dan lebih luas akan kalah dengan kitab yang lebih sedikit dan lebih ringkas disebabkan tidak adanya keikhlasan. Oleh karenanya, ikhlas menempati posisi paling penting dalam sebuah ibadah maupun amal saleh lainnya.
Selain kisah di atas, ada kisah lain yang memposisikan ikhlas di ruang paling inti. Kisah ini menjadi salah satu teladan bagi manusia, bahwa keabadian dalam beramal atau berkarya khususnya tergantung bagaimana memposisikan ikhlas. Jika Allah yang menjadi pokok paling inti dalam amalnya, maka upaya dan jerih payahnya akan berkelanjutan bahkan sampai hari kiamat tidak akan terputus.
Syekh Shanhaji dan Ikhlasnya dalam Berkarya
Siapa yang tidak kenal dengan kitab Matan al-Ajurumiah atau biasa cukup disebut Jurumiyah? Salah satu kitab nahwu yang sangat populer dalam dunia pendidikan, khususnya pesantren. Kitab sederhana dan ringkas ini menjadi pelajaran pokok di hampir semua pondok pesantren. Penjelasannya tidak terlalu luas dan lebar, akan tetapi manfaat dan berkah di dalamnya sangat banyak. Bahkan, orang-orang yang hendak bisa baca kitab kuning, terlebih dahulu mempelajari kitab ini.
Luasnya manfaat dan banyaknya keberkahan kitab Jurumiyah tidak lepas dari peran penulis yang begitu ikhlas ketika menulis. Ia berupaya menghilangkan manusia dalam benak pikirannya dan murni menjadikan Allah sebagai tujuannya. Ia tidak membutuhkan pujian maupun tepuk tangan dari orang lain, yang ia inginkan hanyalah ridha dari Allah swt.
Penulisnya adalah Syekh Shanhaji. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Ajurrum as-Shanhaji. Beliau dilahirkan di kota Fes, Maroko, tahun 672 H, dan wafat pada tahun 723 H. Namanya dikenang sepanjang masa disebabkan karyanya yang sangat sederhana namun ada keikhlasan di dalamnya, sehingga karyanya terus berlanjut dan dipelajari oleh umat Islam.
Imam Kafrawi dalam Syarah kitab Jurumiyah, menyebutkan perihal keikhlasan Syekh Shanhaji ketika menulis kitabnya. Menurutnya, ketika Syekh Shanhaji hendak menulis kitabnya, ia menghadap kiblat dan memohon kepada Allah untuk memberikan manfaat dan keberkahan di dalam karyanya. Ketika beliau berhasil merampungkannya, beliau justru membuang kitab yang sudah ditulisnya ke tengah lautan, kemudian berkata,
اِنْ كَانَ خَالِصًا لِوَجْهِ اللهِ تَعَالَى فَلَا يَبْلُ
Artinya, “Apabila (kitab ini) murni ikhlas semata karena Allah swt, maka (tentu) tidak akan basah” (Imam Kafrawi, Syarah al-Ajurumiyah, [Maktabah al-Hidayah, Surabaya], h. 27).
Atas izin Allah dan berkat keikhlasan Syekh Shanhaji dalam beramal, kitab Ajurumiyah yang ditulisnya tidak basah sedikit pun, bahkan banyaknya air di samudera tidak membekas pada kitab tersebut. Ajurumiyah tetap utuh sebagaimana sebelum dilempar pada lautan. Masyaallah.
Dua kisah di atas, semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita, bahwa ikhlas menjadi penentu suatu usaha akan terus berlanjut atau tidak, terus berkembang dan tidak. Kitab Muwattha’ yang ditulis oleh Ibnu Abi Dza’bi dengan penjelasan yang sangat luas dan detail, justru kalah keberkahannya dengan kitab Muwattha’ yang ditulis oleh Imam Malik, sekalipun penjelasan dan isinya lebih ringkas dan sederhana. Kita bisa melihat saat ini, Muwattha’ Imam Malik begitu manfaat bagi umat Islam, bahkan tidak sedikit para ulama yang mensyarahi kitab ini.
Begitu juga dengan kitab Ajurumiyah, kitab kecil dan sangat ringkas dalam ilmu nahwu begitu berkembang dan berkelanjutan, tidak sedikit para ulama yang mensyarahi menjadi kitab yang lebih luas dan lebih detail. Meski demikian, syarah-syarah Jurumiyah tidak mempengaruhi keberkahannya, ia tetap menjadi kitab pokok sekali pun sudah disyarahi berjilid-jilid.
Ustadz Sunnatullah, Pengajar di Pondok Pesantren Al-Hikmah Darussalam Durjan Kokop Bangkalan Jawa Timur.
Sumber: NU Online